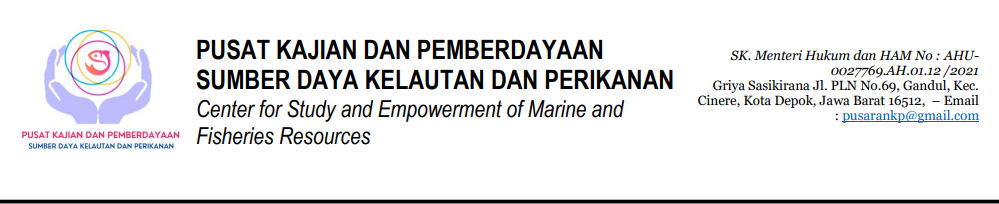Hukum positif akan bertaji jika digali dari unsur kearifan lokal. Kami simpulkan demikian, karena faktanya demikian. Sayang birokratik otoritarian melunturkan makna kearifan lokal itu sendiri.
Pun halnya polemik berkaitan dengan aturan tata kelola sumber daya KP yang muncul ke permukaan publik, salah satunya karena belum sepenuhnya mengkaji dan mempertimbangkan aspek sosial-kultur yang berlaku pada masyarakat pesisir. Termasuk perangkat hukum lokal/adat, yang mestinya jadi dasar hukum positif yang dibuat Pemerintah. Dalam konteks hukum, mewujudkan masyarakat yang mampu ADS (Atur Diri Sendiri) adalah bukti bahwa hukum tersebut efektif. Demikian sebaliknya.
Maka, pada faktanya justru hukum sosial yang berlaku di masyarakat lokal/adat termasuk hukum tak tertulis lebih banyak ditaati ketimbang hukum positif.
Perlu difahami ahwa pemilik hak dominan atas pengelolaan sumber daya KP adalah masyarakat lokal/adat, dan Pemerintah adalah pemilik mandat kolektif untuk melakukan pengaturan atas nama rakyat. Masyarakat dimaksud adalah rumah tangga KP, bukan korporasi besar semata. Maka hak masyarakat lokal/adat betul betul harus dihargai, karena merekalah yang berhubungan langsung dengan sumber daya. Mereka lebih tahu bagaimana memanfaatkan, dan melestarikan atas dasar nilai nilai moral kearifan lokal.
Belajar dari Kearifan Lokal
Kami mencontohkan sebuah unsur kearifan lokal yang ada dalam hukum masyarakat lokal/adat. “Awig-awig” adalah aturan lokal yang berlaku pada masyarakat adat sasak (Lombok) dan Bali. Di Lombok, “Awig-awig” dijadikan sebuah norma dalam mengelola sumber daya perikanan. Pengaturan tangkap berdasarkan musim dan ketentuan lainnya yang mengikat secara sosial menjadi sangat efektif dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Penghargaan terhadap sumber daya dan lingkungan adalah hal mendasar yang berlaku secara turun temurun.
Persisnya, sebenarnya hukum positif harus selaras dan bersumber dari nilai moral yang berlaku di masyarakat, karena masyarakat lokal/adat sebagai objek justru telah memiliki hukum sendiri yang mereka gali dari sumber sumber kerarifan lokal. Kata “arif” mengandung makna kebijaksanaan dalam menempatkan keseimbangan tiga pilar utama sustainability yakni ekologi, ekonomi dan sosial.
Sekali lagi, penting saat ini memupuk nilai nilai ini agar tumbuh subur di daerah daerah basis sumber daya KP. Atau ekstrimnya pembuat aturan mesti belajar banyak bagaimana inisiatif pola pengelolaan sumber daya KP ini dilakukan. Pengaturan pemanfaatan sumber daya KP pada musim musim tertentu, memberikan jeda waktu sumber daya ikan untuk recovery dan memulihkan kondisi seimbang, sehingga siklusnya terus berjalan. Konsepsi ini, akan sangat efektif jika diterapkan dalam konteks pemanfaatan sumber daya lobster misalnya.
Pertanyaanya bagaimana jika korporasi besar berkepentingan mengelola sumber daya yang ada?
Korporasi besar bisa terlibat dalam memanfaatkan kue sumber daya, dengan catatan tidak mengurangi akses masyarakat untuk mendapatkan kue sumber daya yang ada. Sayang, setiap korporasi tujuan utamanya meraup untung dan itu wajar. Ketidakwajaran bisa nampak, saat sumber daya tak lagi terasa manis. Oleh karena itu, disini pentingnya memberlakukan hukum positif yang bersumber dari nilai moral kearifan lokak yang berlaku pada masyarakat hukum adat.
Pemberlakuan pola pemanfaatan perikanan secara terukur berbasis kuota dan stock assesment menjadi langkah awal yang baik sebagai manifestasi dari unsur kearifan lokal yang berlaku. Saat ini mutlak memperkuat kelembagaan masyarakat hukum adat beserta hukum yang berlaku pada mereka.
Sumber gambar : bintangnews.com