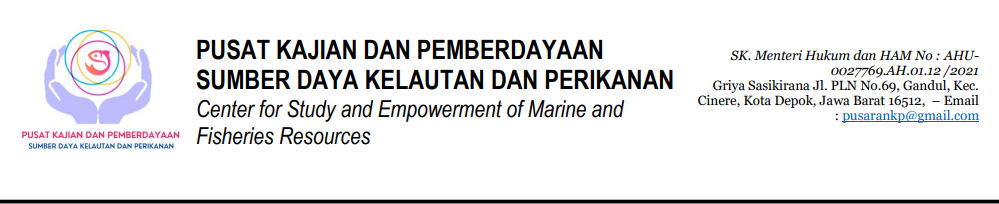Apa Kabar Minapolitan?
Pada 28 Oktober 2015, kami inisiatif mengundang Prof. Hattah Fattah untuk memberikan pengantar diskusi mengenai konsep minapolitan. Kebetulan, lokasi yang kami dampingi saat itu adalah kawasan minapolitan. Sementara, dalam benak saya, kemungkinan masih banyak petambak tradisional yang kurang paham atau tidak paham dengan istilah ini. Ada baiknya dibuka forum, agar terdapat penjelasan serta input dari warga, bagaimana sebaiknya kawasan perikanan itu dikelola?
Dalam diskusi itu, Prof Hatta mengatakan minapolitan mendorong adanya aliran bahan baku perikanan dari desa ke kota, serta aliran uang dari kota ke desa. Sehingga terbentuk ketergantungan fungsional antara desa dan kota, demi tujuan ketahanan pangan. Serta mengarah pada terbentuknya kota-kota kecil berbasis perikanan (minapolis) sebagai bagian dari sistem perkotaan, dengan maksud meningkatkan pendapatan kawasan pedesaan.
Dari konsep itu, Prof Hatta menjelaskan kelebihan-kelebihan kawasan Minapolitan LOWITA (Lotangsalo, Wiringtasi, Tasiwalie) Suppa. Diantaranya terdapat lebih dari 10 hatchery, terdapat potensi komoditas lokal, diantaranya udang windu, pakan alami udang windu yaitu phronima, hingga komoditas cacing laut (nereis sp) untuk digunakan sebagai pakan induk udang. Keunggulan ini katanya harus dikelola berdasarkan prinsip minapolitan, yaitu integrasi, efisiensi dan mengedepankan kualitas.
Pada pertemuan, Prof Hatta pun menjelaskan bahwa sebentar lagi akan terdapat sekolah lapang Phronima, yang akan mendistribusi pengetahuan dari petambak ke petambak. Sekolah Lapang ini pun ke depannya menjadi tandem dari Sekolah Tambak yang kami buat ini.
Pasca pengantar, terdapat pertanyaan dari seorang petambak, yang menanyakan bagaimana cara budidaya udang di tengah-tengah kondisi iklim tahun itu (2015) berupa kemarau berpanjangan? Prof Hatta menjawab, kita akan bantu dengan mengundang BMKG untuk menyediakan data perubahan iklim kawasan Suppa Pinrang.
Lantas, apa yang terjadi pada kawasan minapolitan Lowita, kawasan yang menempati posisi 3 di level nasional, setelah pertemuan ini? Tidak perlu begitu lama menunggu, pasca menurunnya produksi udang windu, dan tergantikan dengan udang vannamei di tahun depannya, minapolitan ini pun mendadak sunyi.
Bibit melemahnya sudah terasa pada pertengahan 2014, ketika terjadi kegagalan dalam proyek percontohan budidaya udang vannamei untuk revitalisasi pertambakan nasional, seluas 20 hektar di Lotangsalo, Suppa, Pinrang. Program ini merugikan keuangan negara sekitar Rp. 360 juta. Beragam alasan yang menjadi penyebab, ada yang bilang kualitas pakannya, ada yang bilang kualitas bahan baku plastiknya. Pastinya, pada 2 September 2014 itu, Bupati, Kadis DKP, dan perwakilan DJPB terlihat kecewa dengan kegagalan itu. Dimana pada 14 Mei 2014, seluruh stakeholder pengelolaan kawasan minapolitan berkumpul di Kantor Bupati Pinrang, dan tampak menggebu-gebu, untuk mensukseskan revitalisasi tambak yang dianggap kurang vital itu. Pun hingga terakhir kali saya melewati kawasan tambak itu, saya masih melihat sisa-sisa plastik tambak, yang menjadi saksi bisu kegagalan bersama revitalisasi tambak Suppa, Pinrang.
Pada akhirnya yang bertahan dari program minapolitan ini hanyalah program pengembangan kawasan wisata, dan ini pun tidak berkaitan dengan ikan/udang. Tidak lama kemudian, konsentrasi pemerintah pun beralih dari Lowita Suppa, ke pusat udang windu yang baru, yaitu Lanrisang-Jampue, di sana tidak lagi bernama Minapolitan, tapi lebih ke nama program pendampingan LSM pendamping perusahaan udang windu, yaitu Ecofarming/ecoshrimp. Semangat bersama untuk membangun kawasan minapolitan sayup-sayup redup, dengan berkurangnya udang windu, dan kurang ampuhnya phronima dalam menahan laju kematian windu di tambak. Meski, vannamei dianggap lebih rasional saat itu bagi para petambak tradisional, yang masih bergantung pada modal minim, dan hanya dengan sewa menyewa tambak.
Petambak udang vannamei pun tidak pusing dengan menghilangnya minapolitan bersama eksponen-eksponennya. Mereka pun makin sibuk dengan aktivitas sehari-hari yang kian bertambah, memberi pakan pada udang, berkeliling 3-6 tambak dalam sehari. Membuat mereka kelelahan dan tidak ada waktu untuk sekadar mengingat konsep minapolitan.
Amnesia di level petambak, diperparah lagi di level pusat, dimana ganti kementerian, ganti konsep. Minapolitan pun menjadi asing dan sangat jarang untuk dibicarakan.
Minapolitan ini pada prinsipnya mengandaikan adanya pusat-pusat produksi, serta berlangsungnya kerjasama antar sektor/instansi/lembaga untuk memutar ekonomi dalam kawasan. Hanya saja, sayangnya, kelembagaan petambak ataupun pendukung petambak di lokus-lokus kawasan minapolitan begitu rapuh.
Barangkali, kita mengandaikan mereka seperti masyarakat pertanian pada umumnya, yang gampang di atur. Seperti agropolitan pada kawasan pertanian. Padahal, minapolitan ini adalah kawasan perikanan, yang masyarakatnya menerapkan cara-cara petani sawah/kebun, namun terperangkap dalam kebiasaan dan pola hidup nelayan/penangkap/pemburu ikan.
Ini sesuai dengan penjelasan Awi Mn, yang mengatakan bahwa petambak udang/ikan berada di antara budaya bertani sawah (agriculture) dan para nelayan/pelaut (marineculture). Situasi transisi ini menyebabkan terdapat ciri khas karakter petambak, yang mirip dengan nelayan pada umumnya. Seperti diungkapkan oleh Arham Ansyhar, ketika saya berdiskusi dengannya kemarin di kantor Sulawesi Community Foundation (SCF), bahwa terdapat kemungkinan bahwa petambak ini hanyalah cerminan kabur dari nelayan. Karakter nelayan adalah karakter masyarakat mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Nelayan hidup berdasarkan informasi yang dimilikinya, misalnya informasi daerah penangkapan yang terdapat banyak ikan. Masing-masing nelayan memiliki informasi yang berbeda, dan jarang mereka berbagi informasi jenis ini. Sebab, jika mereka berbagi, makan akan terjadi sharing poverty (berbagi kemiskinan). Itulah sebabnya, nelayan begitu sulit disatukan dalam sebuah kelompok/lembaga nelayan.
Etos ini pun barangkali juga masih melekat di kehidupan petambak. Sebab, petambak tak lain adalah nelayan di masa lalunya. petambak hari ini adalah seorang anak dari ayah nelayan di masa lalu. Atau petambak hari ini adalah sekaligus nelayan. Masih banyak saya temukan petambak yang juga memiliki perahu, dimana pada waktu-waktu tertentu, para petambak juga pergi melaut untuk menangkap ikan, untuk menambah pundi-pundi ekonomi mereka.
Sehingga, model kelompok, ataupun minapolitan untuk skala besarnya, saya kira memang perlu dikoreksi kembali. Untuk menemukan pola dan cara-cara yang tepat dalam pendampingan masyarakat pesisir. Apakah mungkin, para petambak/nelayan ini tidak perlu dipaksa berkelompok. Tapi, yang mesti dipaksa adalah bersekolah? Entah sekolah tambak atau sekolah lapang, dimana mereka tidak perlu berbagi, tapi tetap memperoleh input untuk peningkatan kapasitas diri sendiri, masing-masing petambak/nelayan itu sendiri.
Lalu, di suatu ketika terdapat situasi mereka merasa-rasa sudah harus bekerjasama, misalnya ketika terjadi bencana, wabah, atau apa pun itu. Di saat-saat itulah diperlukan kepemimpinan, untuk mengarahkan mereka untuk bekerjasama, mengatasi permasalahan bersama.
Penulis :
Aquaculture Specialist- WWF Indonesia
Analis Senior – Pusaran KP