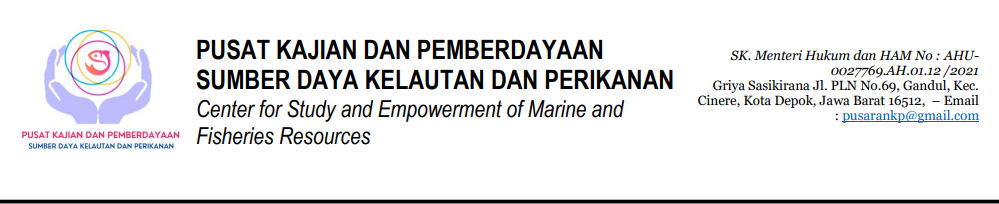Ketika ngobrol mengenai induk udang, kita mungkin mengingat Aceh. Kota Serambi Mekah yang pernah mengalami tragedi naas, tsunami akhir tahun 2004. Dalam bayangan kita, induk Aceh, tanpa perlu memperjelas bahwa induk itu hanya ada di sekitar perairan Muara Kuala Boekah, Langsa dan di pesisir Aceh Timur, adalah induk terbaik di Indonesia. Hingga pendataan yang kami lakukan pada 2019, Induk Aceh masih diminati dengan sangat oleh hatchery-hatchery besar di Sulawesi Selatan. Lantas ada apa dengan induk Aceh ini?
Pada 25 Mei 2013, Saya pernah menemui salah satu pengirim induk udang terbesar asal Langsa, namanya H. Ismail HZ. Rumahnya bak istana, halaman cukup luas, kita bisa bayangkan rumah Ismail dengan rumah-rumah pengusaha ikan terbang yang ada di Galesong Takalar. Kami bercerita mengenai kondisi induk udang windu saat itu.
“Sekarang nelayan hanya menangkap 8-10 ekor perhari. Dulu (1990-an) bisa sampai 20-30 ekor perhari,” kata Ismail, yang saat itu memperlihatkan cicin besar yang ada di jari manisnya. Bahkan, jika dikumpulkan semua nelayan yang menangkap induk di Muara Boekah Langsah bisa sampai 500 ekor perhari. Ia pun mengatakan bahwa dulu harga induk udang bisa sampai Rp. 1,2 juta perekor dan sekarang tersisa Rp. 80-120 ribu. Perahu-perahu yang turun menangkap induk udang juga jauh turunnya. Tersisa 3 perahu perhari, padahal pada 1990-an itu bisa sampai 30 perahu perhari.
Memang, sejak merebaknya virus WSSV (White Spot Syndrom Virus) yang menjungkal pebisnis-pebisnis udang windu, turut melemahkan ekonomi nelayan-nelayan penangkap induk udang Langsa, disebabkan menurunnya permintaan induk udang windu. Hatchery-hatchery (balai benih udang) akhirnya banyak mengganti udang windu ke udang vannamei, lantaran begitu massifnya kegagalan panen udang di tingkat petambak baik skala padat modal/intensif maupun skala tradisional. Lantas, apakah juga karena itu?
Dr. Ir. Andi Parenrengi, MSc, mantan kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Maros pernah mengatakan bahwa sejak 2015, induk udang Aceh mengalami penurunan kualitas genetik. Selain itu, Ir. Muharijadi Atnomarsono, MSc, juga dari Balai Maros mengatakan induk udang Windu dalam beberapa kali sampel terdeteksi penyakit WSSV, mulai dari level 10% hingga 100%. Beberapa minggu lalu, saya berdiskusi lagi dengan salah satu peneliti Balai Maros, yaitu Agus Nawang, katanya, tidak selalu induk udang teridentifikasi WSSV, tapi pada musim-musim tertentu saja. Kadang bagus, kadang juga jelek, katanya.
“Sayangnya, induk udang ini hanya ada di area perairan itu saja, semakin sulit menemukan induk udang selain di area itu,” kata Agus berdasarkan hasil kunjungannya belum lama dari pesisir timur Aceh.
Dari satu wawancara dengan tokoh pembudidaya dalam film pendek yang dibuat oleh WWF-Indonesia diperoleh gambaran salah satu faktor berkurangnya induk udang windu asal Aceh. “Kalau dulu, mayoritas di wilayah tambak kita di sini, hutan mangrove sekitar 70%, berkurangnya bakau di wilayah pesisir, air menjadi makin keruh, udang windu (induk) lari juga makin jauh ke sana, karena kualitas air kurang bagus,” kata Busra, pembudidaya udang. Memang dalam film itu tidak disebut penyebabnya, cuma terlihat hamparan luas kebun sawit mengisi atau mengganti hamparan yang sebelumnya sebagian adalah ekosistem mangrove.
Boleh jadi, perkebunan sawit inilah yang jadi salah satu penyebab, meski tidak bisa dituduh secara langsung bahwa ia sebagai penyebab utama. Kita tidak tahu, seperti apa penggunaan pupuknya, penggunaan jika dipakai_pestisida-nya. Kalau dalam penjelasan Busra, air menjadi kian keruh. Kekeruhan saja, bisa menjauhkan induk udang, apalagi ditambah limbah pupuk dan campuran-campuran kimia lainnya.
Induk udang windu Aceh di kirim ke kantong-kantong budidaya udang windu di seluruh Indonesia, seperti Rembang, Surabaya, Lampung, Makassar. Di Makassar saja, pada pendataan kami pada Januari-April 2019, terdapat sekitar enam hatchery besar dan kecil (backyard) yang membeli induk udang Aceh. Seperti PT. Surya Monodon Takalar bisa sampai 100-200 ekor perpengiriman dengan produksi benur 10-40 juta ekor benur, begitu halnya PT. Puncak Sinunggal Barru hingga BBU Suppa Pinrang, yang produksinya 10-25 juta benur. belum lagi bacyard, yang walau tidak membeli induk, tapi memanfaatkan naupli dari hasil pemijahan induk udang Aceh.
Hingga 2018, ketiga hatchery besar yang telah disebutkan itu masih komitmen untuk memproduksi udang windu, dengan menggunakan induk Aceh. “Selama 16 tahun ini kita bertahan di windu. Cuma ada pengaruh-pengaruh, yaitu udang vannamei. Disebabkan oleh promosi yang bagus, kalkulasi atau perhitungan bisnis yang dianggap menguntungkan. Dampaknya bagi pembelian benur windu terasa sekali dalam 3 tahun ini. Tapi, saya pikir-pikir, pindah ke vannamei, istilahnya tidak kena. BBU tidak akan beralih ke vannamei. Karena, saya juga baca situasi pasar,” kata Ujang, pengelola hatchery BBU Suppa.
Itu wawancara tiga tahun lalu, saya mendengar, Pak Ujang sudah mulai coba-coba Vannamei. Dia tak tahan hantaman yang begitu keras, mulai dari induk udang baik aceh maupun lokal yang kualitasnya menurun, juga hantaman pasar udang windu yang menurun drastis.
Apalagi pada suatu waktu di 2018, yaitu Senin, 26 November, sebanyak 150 ekor induk betina dan 50 ekor induk jantan mati lemas dalam perjalanan menuju Bandara Sultan Hasanuddin. Rencananya induk ini akan digunakan oleh tiga hatchery itu (Surya Monodon, Puncak Sinunggal dan BBU Suppa). Penyebab kematian induk itu karena terlalu lama tertahan di Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan kurang penanganan serius saat fase menunggu. Efeknya pada tertundanya kegiatan pemeliharaan udang windu di tingkat petambak, karena hatchery otomatis terpaksa mencari sumber-sumber induk lain, seperti induk lokal, dengan konsekuensi kualitas benur yang lebih rendah. Saat itu, diperkirakan kerugian pengelola hatchery ada sekitar Rp. 40 juta.
Berbagai sumber penyebab, baik induk udang, maupun kualitas perairan yang ada di Sulawesi Selatan, juga faktor langsung berupa kematian udang windu, mendorong para petambak untuk beralih ke udang vannamei. Dari data survei udang windu terbaru, ditemukan bahwa area budidaya udang windu tersisa di beberapa daerah saja, seperti Makassar (Lakkang dan Parangloe) serta Pinrang yaitu daerah Lanrisang serta sebagian kecil daerah Maros dan Pangkep, selebihnya adalah kantung-kantung yang telah didominasi oleh udang vannamei. Ironisnya, sebagian besar udang windu yang terjual ke coldstorage di KIMA Makassar adalah udang dari Batu Licin, Kalimantan Selatan. Udang dari Batu Licin bisa sampai 10.000 kg perbulan.
Bagaimana mengatasi ini? Sebenarnya pemerintah pernah melakoni sebuah inisiatif, yaitu penelitian untuk menghasilkan induk udang yang dapat memperoduksi benur SPR (Spescific Pathogen Resistent), diemban oleh Cabang Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Maros, di Siddo-Lawellu, Kab. Barru.
Sayang saja, inisiatif yang membutuhkan energi jangka panjang itu berhenti di tengah jalan, lantaran bergantinya kebijakan di level kementerian. Seandainya saja Pemerintah Indonesia dapat memfokuskan diri pada pengembangan induk dan benur yang bebas penyakit, melalui skema R&D (Research and Development) yang tahan banting, terbentur-terbentur, terbentuk. Namun, untuk kasus ini, hanya terbentur dan terbentur lagi.
Belum lagi pengamanan kantung-kantung induk udang windu. Apakah telah dilakukan mekanisme pengelolaan kawasan induk udang secara baik, misalnya di Muara Boekah, Langsa, Aceh Timur? Apakah sudah terdapat data yang lengkap mengenai potensi induk udang yang ada di sepanjang pesisir Indonesia? Apakah telah dilakukan pendidikan/pelatihan kepada para nelayan penangkap induk udang agar dapat menangkap dengan baik dan menjamin kualitas induk udang terjaga karena tidak stress? Apakah terdapat dorongan kepada pengusaha-pengusaha muda, untuk melakukan eksplorasi terhadap induk-induk lokal non Aceh agar dapat menjadi pembanding dengan induk Aceh?
Apalagi saat ini, pada pertemuan RAKOR Pengembangan Kluster Udang Nasional di Makassar, 13-15 Oktober 2020, terdapat target peningkatan produksi udang nasional sebesar 250 persen pada 2024. Dimana Sulsel harus meningkat dari 31.985,5 ton menjadi 79.963,75 ton pada 2024. Tentu, strategi ini ditujukan pada udang vannamei, yang bisa dipelihara secara intensif dan supraintensif.
Namun, sama halnya dengan windu, seperti apakah pengelolaan induk udangnya? Hatchery-hatchery besar di Indonesia maupun menengah dan kecil masih bergantung pada induk impor, yaitu dari Hawai-Amerika, seperti di Konabay maupun lembaga risetnya seperti Oceanic Institute di Hawai Pacific University.
Padahal pemerintah sejak 2010, telah mencoba untuk memproduksi induk udang vannamei sendiri di BPIU2K (Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan) Karangasem Bali, yang disebut Induk Udang Nusantara. Namun, hingga 2021 ini atau 11 tahun setelah melalui upaya ujicoba, belum juga menunjukkan hasil yang sama dengan induk udang dari luar. Hatchery udang vannamei lebih memilih membeli induk luar, karena kualitas lebih bagus.
Ketergantungan induk udang vannamei dari luar, menjadikan petambak udang nasional kita sangat rentang untuk tumbang, jika terdapat goncangan politik ekonomi dengan negara sumber induk misalnya Amerika Serikat. Sedangkan, kurang dikembangkannya induk udang windu, dan kurangnya perhatian pada pengelolaan lingkungan pada kawasan induk udang windu di Langsa dan Aceh Timur, dengan membiarkan kehancuran ekologis di sana. Bukannya menjadikan kita penuh berharap untuk kebangkitan udang windu.
Hal-hal seperti inilah yang kadang membuat saya bersedih, dan tak tahu harus berbuat apa. Dan, dengan menulis ini, barangkali dapat sedikit mengatasi kegundahan saya mengenai problem induk udang ini, baik udang windu maupun udang vannamei.
**
Foto : pengukuran induk udang di halaman rumah Pak Ismail, di Langsa, Mei 2013.
Penulis :
Idham Malik
Aquaculture Specialist WWF Indonesia
Analis Senior Pusaran KP