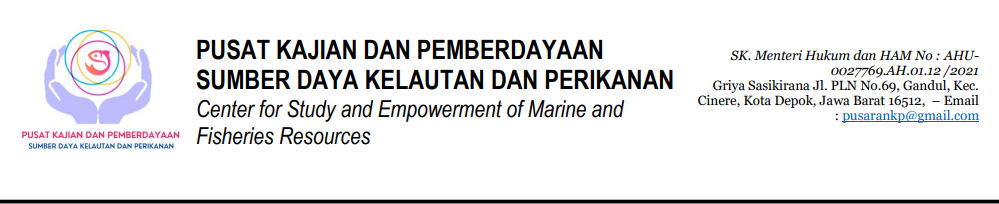Mengutip dari data Ocean Health Index/OHI tahun 2022, Indonesia menempati peringkat 181 dari 220 negara yang memiliki wilayah laut tersehat. Selama kurun waktu tahun 2012-2022 rata rata indeks OHI dunia berada pada skor 69 (dari skala 100), dan Indonesia berada jauh lebih rendah dengan skor 63. Jika melihat rata rata skor dunia, terlihat bahwa kondisi laut secara global sedang tidak baik baik saja. Pun halnya dengan Indonesia bahkan angkanya lebih rendah lagi, padahal negara kita 2/3 nya merupakan wilayah laut.
Laut memiliki nilai strategis penting, terutama sebagai sumber penyedia produk pangan dan alam ditengah terpaan isu krisis pangan global yang menghantui. Dengan biodiversitas tinggi, laut menjadi penyuplai utama kebutuhan pangan global. Praktek-praktek pemanfaatan sumber daya laut menjadi salah satu isu yang saat ini menjadi perhatian global. Fakta menyurunnya indeks kesahatan laut, tentu menjadi kekhawatiran nyata terhadap penurunan produktivitas laut, dan pada ujungnya akan menjadi ancaman nyata bagi global food security.
Terjadinya paradoks ekologi, sepertinya semakin tidak disadari. Laut masih dilihat dari aspek sumber daya ekonomi, sehingga pola pemanfaatan sumber daya alam lebih cenderung eksploitatif, padahal disatu sisi memberikan dampak signifikan terhadap kelestarian ekosistem laut itu sendiri. Teori butterfly effect patut menjadi bahan renungan masyarakat global, bahwa perubahan sekecil apapun akan mengakibatkan dampak besar dalan jangka waktu yang panjang. Sangat mengerikan jika ini terjadi pada lingkungan laut dimana masyarakat global tergantung pada sumber daya dan lingkungan laut.
Melihat data OHI Indonesia yang memiliki skor rendah, menunjukkan bahwa kualitas lingkungan laut Indonesia juga sedang tidak baik baik saja. Penulis mencoba fokus pada pembahasan dua indikator yang menjadi faktor pengungkit dan memiliki nilai merah (skor 23,8) yaitu terkait ketersediaan laut sebagai sumber makanan dan indikator parawisata laut yang memiliki skor 29. Dua indikator paling rendah ini menjadi warning bagi kita, terutama jika dikaitkan dengan fakta berbagai masalah yang tengah di hadapi Indonesia saat ini.
Dari sisi parameter laut sebagai sumber pangan, assesmen OHI menyimpulkan Indonesia belum sepenuhnya melakuan optomalisasi pemanfaatan sektor perikanan yang berbasis pada praktek pengelolaan perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries) termasuk subsektor akuakultur. Sebenarnya Indonesia telah memiliki legal framework sebagai bentuk implementasi amanat dalam FAO Code of Conduct. Masih terjadinya IUU fishing dan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, nampaknya menjadi faktor utama penyebab nilai merah pada indikator ini. Kondisi ini juga bisa disandingkan dengan data kerentanan stok di seluruh WPPNRI yang secara umum telah over eksploitatif. Perairan laut sebagai wilayah yang dianalogikan sebagai common property, maka Pemerintah harus lebih efektif dalam melakukan pengaturan dan pengawasan, terutama dalam menghindari persaingan pemanfaatan sumber daya laut yang kerap terjadi antara korporasi dengan masyarakat nelayan kecil. Ruang laut sebagai common property akan memicu persaingan sumber daya (rivarly natural resources) dan ini menjadi ancaman bagi keseimbangan ekosistem laut.
Menariknya, nilai OHI Indonesia justru terdongkrak oleh indikator dalam bidang perikanan skala kecil/lokal. Penerapan perikanan skala kecil/lokal justru dinilai telah sesuai dengan konsep perikanan berkelanjutan. Fakta ini bisa kita lihat bahwa masyarakat nelayan tradisional justru lebih faham bagaimana mengelola sumber daya perikanan secara bertanggungjawab dengan menjadikan local wisdom sebagai perangkat hukum tak tertulis. Penerapan konsep aturan adat seperti awig awig di NTB, adat sasi di Maluku adalah bagian dari implementasi konsep perikanan terukur. Biota laut sebagai sumber daya sekaligus bagian dari ekosistem membutuhkan waktu jeda untuk pemulihan (menyeimbangkan diri). Masyarakat tradisional sangat faham dengan siklus alamiah ini. Oleh karenenya, keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) mutlak untuk diberi ruang luas dalam rangka mengoptimalkan sumber daya perikanan dengan tetap mempertahankan kesehatan laut. Akan lebih efektif jika perangkat hukum positif digali dari konsep kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat tradisional di pesisir.
Indikator kedua yang memiliki nilai merah yakni parawisata laut terutama dalam kaitannya dengan kelestarian ekosistem laut. Ancaman terhadap ekosistem laut kian nyata. Meningkatnya aktivitas/kegiatan ekonomi di inland seperti industri, pertambangan, mass tourism, perumahan dan aktivitas anthropogenik lain telah secara nyata memicu kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Efek global warming juga sebenarnya dipicu oleh industrialisasi di wilayah inland, dimana dampaknya secara langsung menggangu keseimbangan ekosistem laut. Hilangnya ekosistem penyangga (mangrove, lamun, dan terimbu karang) menjadi fakta yang tak terbantahkan terjadi di berbagai wilayah. Maraknnya aktivitas pertambangan di wilayah pesisir, seperti di Halmahera menjadi momok menakutkan, karena faktanya beban cemaran juga masih dibuang ke perairan, ini menyebabkan ekosistem terumbu karang rusak, produktivitas periaran menurun, dan hasil tangkapan nelayan menjadi turun drastis. Berita harian kompas edisi 7 November 2023, menyebutkan fakta bahwa perairan Halmahera sudah tercemar logam berat akibat aktivitas tambang. Jika sudah begini, maka bagaimana mau bicara pangan berkelanjutan ? isu pencemaran logam berat akan berdampak pada foodsafety dan secara ekonomi akan berdampak pada keberterimaan produk perikanan RI.
Indonesia juga masih berperang melawan sampah plastik. Salah satu masalah utama yang merusak kesehatan laut yakni sampah plastik. Dampak sampah plastik dan micro plastik di perairan sangat besar dan menjadi ancaman bagi kelestarian ekosistem dan biota laut sebagai sumber pangan masa depan. Dikutip dari data Kementrian Kelautan dan Perikanan, Indonesia masuk urutan kedua penyumbang sampah plastik di dunia pada tahun 2019, dimana sebanyak 3,21 Juta metrik ton/tahun di buang ke laut. Ironisnya, meski Indonesia menjadi penyumbang terbesar sampah plastik, namun dilihat dari indek pengelolaan sampah plastik, Indonesia berada di urutan ke 16 dari 25 negara di dunia, bahkan tertinggal dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia (sumber : Plastic Management Index, 2020).
Dalam ajang One Ocean Summit 2023 bulan Maret lalu dalam pidatonya Presiden Joko Widodo menuturkan komitmen Indonesia dalam perlindungan laut melalui pencapaian target kawasan konservasi laut seluas 32,5 juta hektar di tahun 2030 dan komitmen untuk mengurangi sampah plastik sebesar 70% di tahun 2025. Komitmen Presiden ini tentu harus benar benar jadi fokus implementasi. Pemberlakuan UU Minerba beserta produk turunannya, serta kebijakan proyek strategis nasional (PSN) hendaknya selaras dengan komitmen pada ajang One Ocean Summit di atas. Catatan kritis baik dari ilmuan maupun para penggiat lingkungan mesti dijadikan nutrisi. Konsepsi blue economy, semestinya bukan hanya pada tataran konsep, tapi betul betul tercermin dalam setiap pendekatan pengelolaan sumber daya alam.
Basis data juga hendaknya harus berbasis kajian mendalam dan fakta empiris, dan bukan berdasarkan pada asumsi. Oleh karena itu, keterlibatan pemangku kepentingan mutlak dilakukan. Dari aspek yuridis, hendaknya juga selaras dengan peraturan perundangan lainnya, karena dalam kontek laut, ada multi sektor yang terlibat. Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh tumpang tindih atau bahkan kontraproduktif dengan perundang-undangan lainnya. Sebuah produk hukum hendaknya bersifat terpadu, komprehensif dan menjungjung tinggi prinsip kehati-hatian.
Mari kita jaga, lindungi dan. lestarikan laut kita untuk masa depan antar generasi.